Latar Belakang Terbentuknya Masyarakat Multikultural Di Indonesia
INIRUMAHPINTAR - Indonesia dikenal dunia sebagai negeri multikultural. Lalu, apa saja hal-hal yang menjadi Latar Belakang Terbentuknya Masyarakat Multikultural di Indonesia? Melalui goresan pena ini, mari kita renungi sejumlah faktor-faktor dan unsur-unsur pembeda yang menjadi cikal-bakal hadirnya komunitas multikultural di Indonesia tersebut:
Wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia pun kemudian dihuni oleh masyarakat-masyarakat yang beragam. Mereka hidup dan mencari penghidupan sesuai kontur wilayah yang mereka tinggali. Mereka berinteraksi dan berkarya juga sesuai cerminan wilayah masing-masing.
Salah satu produk utama yang menopang hadirnya masyarakat multikultural yakni bahasa. Setiap wilayah mempunyai perbedaan bahasa. Bahkan, satu masyarakat serumpun sekalipun yang mendiami pulau yang sama terkadang mempunyai bahasa yang tidak serupa. Sekalipun ada yang sama, perbedaan jarak dan wilayah menghasilkan perbedaan kosakata dan dialek
Komunitas yang mendiami area pegugusan gunungan, pantai, persawahan, pasar dan sentra kota tentu mempunyai cara hidup tidak serupa. Karena itulah kita temui beranekaragam profesi, menyerupai petani, nelayan, pegawai, pedagang, dsb. Bahkan, adanya struktur geografis yang tidak serupa (misalnya perbedaan struktur tanah), memungkinkan profesi serupa mempunyai kultur tidak serupa. Dalam hal ini, sesama petani saja belum tentu akan menanam produk pertanian yang sama.
Di profesi lain menyerupai nelayan misalnya, cara mereka menangkap ikan pun belum tentu sama. Pedagang juga begitu. Mereka niscaya akan menjual dagangan tidak serupa dan menjual dengan gaya tidak serupa. Termasuk, konsumen, para pembeli, mereka akan menawar dan membeli dengan kultur tidak serupa.
Selain itu, semua wilayah juga mempunyai tarian perang tidak serupa-beda, yang digunakannya sebagai seni administrasi tes kempuan dan pemahaman yang kondusif untuk melawan penjajah.
Faktor sejarah juga melatarbelakangi efek keyakinan dan kepercayaan setiap etnis masyarakat. Aceh, yang kental dengan efek Islam akan cenderung mempunyai kultur Islam yang kental. Begitupun Bali, yang bersahabat kaitannya dengan kultur Hindu. Masyarakat di wilayah-wilayah lain di Indonesia pun mempunyai proses menyerupai itu.
Termasuk etnis Sumatra yang juga populer bahagia merantau, banyak didatangi di pulau Jawa. Belum lagi adanya contoh transmigrasi yang dicanangkan pemerintah semenjak dulu, mengakibatkan masyarakat multi-etnis dari seluruh Indonesia saling berinteraksi dan membentuk masyarakat yang bervariasi.
Perbedaan kontur infrastruktur, menyerupai jalan raya, tentu menghipnotis tipe-tipe transportasi. Selain itu, perbedaan pemerataan teknologi informasi, juga menghipnotis respon masyarakat terhadap internet dan smartphone. Masyarakat Papua tentu tidak mempunyai ketergantungan yang sama dengan masyarakat Jawa untuk mengakses dunia maya, berkomunikasi via ponsel, atau mencari gosip di media massa.
Jadi, tidak mengherankan lahirnya masyarakat multikultural di Indonesia.
Masyarakat di perkotaan yang mempunyai susukan pendidikan lebih luas tentu akan mempunyai kecenderungan contoh hidup dan kultur tidak serupa. Termasuk dalam persaingan memperoleh pekerjaan.
Jadi, jan cubo cubo heran jikalau masyarakat kota cenderung lebih egois ketimbang masyarakat desa. Dan dari segi budpekerti dan sopan-santun, masyarakat desa cenderung lebih terbuka dan bahagia berinteraksi serta saling tolong-menolong.
Orang-orang yang dulunya beragama dengan baik, sanggup menjadi radikal Istimewa untuk lantaran salah bergaul dan berguru.
Orang-orang yang beragama tapi kaku dan tidak melengkapinya dengan pengetahuan sanggup menjadi sesat dan salah dalam ber-Tuhan.
Kedangkalan beraqidah dan kebodohan yang disebabkan miskinnya ilmu agama dan fakirnya nalar sehat akan memungkinkan lahirnya manusia-manusia yang justru meninggalkan agama.
Akal tanpa agama itu buta, agama tanpa nalar itu tuli. Hidup tanpa agama akan cacat.
Apakah Pancasila sudah layak menjadi pemersatu? Jika ya, mengapa hingga detik ini, kita masih sering mendapati adanya kericuhan akhir perbedaan?
Ayo kita berdiri bangsa kita, mari bergandengan tangan meski kita tidak serupa, tapi ingat! jan cubo cubo hingga melangkahi garis-garis toleransi, terutama dalam hal berkeyakinan.
Stop menilai agama lain dengan ukuran agama sendiri (apalagi dengan menciptakan status di sosial media), kecuali ingin berdiskusi dalam ranah akademik bersama para ahlinya.
Kalau ada yang salah atau berdasarkan kita salah, dahulukan tabayyun. Hilangkan fitnah dan berkelahi domba.
Indonesia tidak memaksa kita untuk sama, dan menyamakan perbedaan, melainkan bagaimana hidup mendapatkan perbedaan.
Jadi, sebagai penutup, jikalau masih ada yang kau dapati melaksanakan acara yang melawan perbedaan, abaikan, jauhi, dan jan cubo cubo bati-bati (cuekin). Biar mereka terkucilkan dan menyadari bahwa Indonesia bukanlah daerah yang pantas buat mereka.
1. Latar Belakang Wilayah
Indonesia ialah negara kepulauan yang memungkinkan hadirnya banyak wilayah-wilayah dengan ciri khas masing-masing. Setiap wilayah dari waktu ke waktu tumbuh menjadi peradaban yang unik dan tidak serupa satu sama lain.Wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia pun kemudian dihuni oleh masyarakat-masyarakat yang beragam. Mereka hidup dan mencari penghidupan sesuai kontur wilayah yang mereka tinggali. Mereka berinteraksi dan berkarya juga sesuai cerminan wilayah masing-masing.
Salah satu produk utama yang menopang hadirnya masyarakat multikultural yakni bahasa. Setiap wilayah mempunyai perbedaan bahasa. Bahkan, satu masyarakat serumpun sekalipun yang mendiami pulau yang sama terkadang mempunyai bahasa yang tidak serupa. Sekalipun ada yang sama, perbedaan jarak dan wilayah menghasilkan perbedaan kosakata dan dialek
2. Perbedaan Struktur Geografis
Perbedaan wilayah juga menjadi latar belakang timbulnya perbedaan struktur geografis. Selanjutnya, perbedaan geografis hadir sebagai salah satu latar belakang terbentuknya masyarakat multikultural.Komunitas yang mendiami area pegugusan gunungan, pantai, persawahan, pasar dan sentra kota tentu mempunyai cara hidup tidak serupa. Karena itulah kita temui beranekaragam profesi, menyerupai petani, nelayan, pegawai, pedagang, dsb. Bahkan, adanya struktur geografis yang tidak serupa (misalnya perbedaan struktur tanah), memungkinkan profesi serupa mempunyai kultur tidak serupa. Dalam hal ini, sesama petani saja belum tentu akan menanam produk pertanian yang sama.
Di profesi lain menyerupai nelayan misalnya, cara mereka menangkap ikan pun belum tentu sama. Pedagang juga begitu. Mereka niscaya akan menjual dagangan tidak serupa dan menjual dengan gaya tidak serupa. Termasuk, konsumen, para pembeli, mereka akan menawar dan membeli dengan kultur tidak serupa.
3. Faktor Sejarah
Masyarakat tumbuh dipengaruhi oleh sejarah peradabannya. Karena hampir semua wilayah Indonesia pernah sama-sama terjajah, maka tidak mengherankan, setiap wilayah mempunyai senjata khas masing-masing yang dulunya dipakai sebagai alat melawan penjajah.Selain itu, semua wilayah juga mempunyai tarian perang tidak serupa-beda, yang digunakannya sebagai seni administrasi tes kempuan dan pemahaman yang kondusif untuk melawan penjajah.
Faktor sejarah juga melatarbelakangi efek keyakinan dan kepercayaan setiap etnis masyarakat. Aceh, yang kental dengan efek Islam akan cenderung mempunyai kultur Islam yang kental. Begitupun Bali, yang bersahabat kaitannya dengan kultur Hindu. Masyarakat di wilayah-wilayah lain di Indonesia pun mempunyai proses menyerupai itu.
4. Faktor Sosial Budaya
Adanya kekhasan sosial budaya juga melatarbelakangi terbentuknya masyarakat multikultural di Indonesia. Budaya merantau yang banyak dipraktikkan masyarakat Bugis Makassar misalnya, mengakibatkan etnis ini hampir selalu ada di bumi Indonesia. Bahkan tidak sedikit rumpun Bugis yang melanglang buana hingga ke mancanegara, menyerupai Malaysia, Brunei, hingga Madagaskar.Termasuk etnis Sumatra yang juga populer bahagia merantau, banyak didatangi di pulau Jawa. Belum lagi adanya contoh transmigrasi yang dicanangkan pemerintah semenjak dulu, mengakibatkan masyarakat multi-etnis dari seluruh Indonesia saling berinteraksi dan membentuk masyarakat yang bervariasi.
5. Faktor Pemerataan Pembangunan
Pemerataan pembangunan juga sanggup melatarbelakangi terbentuknya masyarakat multikultural di Indonesia. Coba bandingkan Jawa dan Papua. Walaupun Papua dikenal dengan penghasil emas terbesar di dunia, toh, ternyata berbanding terbalik dengan kultur masyarakatnya yang masih sangat tertinggal dibandingkan dengan masyarakat di pulau Jawa.Perbedaan kontur infrastruktur, menyerupai jalan raya, tentu menghipnotis tipe-tipe transportasi. Selain itu, perbedaan pemerataan teknologi informasi, juga menghipnotis respon masyarakat terhadap internet dan smartphone. Masyarakat Papua tentu tidak mempunyai ketergantungan yang sama dengan masyarakat Jawa untuk mengakses dunia maya, berkomunikasi via ponsel, atau mencari gosip di media massa.
Jadi, tidak mengherankan lahirnya masyarakat multikultural di Indonesia.
6. Faktor Pendidikan
Perbedaan kualitas pendidikan, mulai dari sarana dan prasarana, kompetensi dan jumlah guru, santunan akomodasi perpustakaan dan internet juga menghipnotis keberagaman masyarakat. Tidak terkecuali hadirnya pendidikan non-formal menyerupai forum bimbingan belajar, kursus, dan pe tes kempuan dan pemahaman keterampilan ikut menjadi latar belakang terbentuknya masyarakat multikultural.Masyarakat di perkotaan yang mempunyai susukan pendidikan lebih luas tentu akan mempunyai kecenderungan contoh hidup dan kultur tidak serupa. Termasuk dalam persaingan memperoleh pekerjaan.
Jadi, jan cubo cubo heran jikalau masyarakat kota cenderung lebih egois ketimbang masyarakat desa. Dan dari segi budpekerti dan sopan-santun, masyarakat desa cenderung lebih terbuka dan bahagia berinteraksi serta saling tolong-menolong.
7. Faktor Pemikiran
Majunya peradaban, majunya pendidikan, dan luasnya daya jangkau manusia, termasuk dalam mengenyam ilmu pengetahuan dan teknologi, membuatnya menjadi manusia-manusia yang multikultural.Orang-orang yang dulunya beragama dengan baik, sanggup menjadi radikal Istimewa untuk lantaran salah bergaul dan berguru.
Orang-orang yang beragama tapi kaku dan tidak melengkapinya dengan pengetahuan sanggup menjadi sesat dan salah dalam ber-Tuhan.
Kedangkalan beraqidah dan kebodohan yang disebabkan miskinnya ilmu agama dan fakirnya nalar sehat akan memungkinkan lahirnya manusia-manusia yang justru meninggalkan agama.
Akal tanpa agama itu buta, agama tanpa nalar itu tuli. Hidup tanpa agama akan cacat.
Kesimpulan dan Penutup
Adanya faktor-faktor yang menjadi latar belakang terbentuknya masyarakat multikultural di Indonesia di atas tentu sangat mempunyai kegunaan sebagai materi renungan dan belajar. Tantangannya adalah, bagaimana kita, masyarakat Indonesia sanggup hidup berdampingan dengan aman, damai, tenteram dengan kondisi tidak serupa-beda?Apakah Pancasila sudah layak menjadi pemersatu? Jika ya, mengapa hingga detik ini, kita masih sering mendapati adanya kericuhan akhir perbedaan?
Ayo kita berdiri bangsa kita, mari bergandengan tangan meski kita tidak serupa, tapi ingat! jan cubo cubo hingga melangkahi garis-garis toleransi, terutama dalam hal berkeyakinan.
Stop menilai agama lain dengan ukuran agama sendiri (apalagi dengan menciptakan status di sosial media), kecuali ingin berdiskusi dalam ranah akademik bersama para ahlinya.
Kalau ada yang salah atau berdasarkan kita salah, dahulukan tabayyun. Hilangkan fitnah dan berkelahi domba.
Indonesia tidak memaksa kita untuk sama, dan menyamakan perbedaan, melainkan bagaimana hidup mendapatkan perbedaan.
Jadi, sebagai penutup, jikalau masih ada yang kau dapati melaksanakan acara yang melawan perbedaan, abaikan, jauhi, dan jan cubo cubo bati-bati (cuekin). Biar mereka terkucilkan dan menyadari bahwa Indonesia bukanlah daerah yang pantas buat mereka.




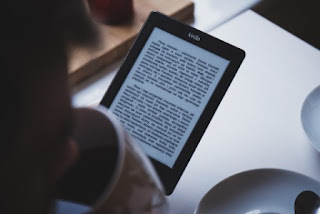
Komentar
Posting Komentar